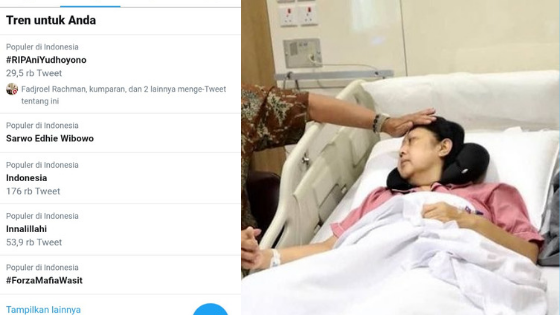Ternyata masalah uang receh bukan masalah kecil, tetapi bisa menjadi krusial dan masif. Walau urusannya seperak dua, tapi masalahnya bisa membuat pusing satu dua menteri, bahkan bisa lebeh.
Seorang abang-abang awak yang dosen sosial politik sebuah PTS menulis di wall-nya, hal yang sering dianggap sepele itu dampaknya bisa sampai ke perhitungan pajak.
Jika harga dibulatkan ke atas perusahaan pasti rugi bayar pajak lebih besar dari yang seharusnya.
Jika harga dibulatkan ke bawah perusahaan dan negara yang jadi sama-sama korban.
Hal ini menurutnya dahsyat dan sistem moneter kita bisa kelimpungan karena tak mampu menyediakan pecahan terkecil mata uang untuk fasilitasi transaksi di tengah masyarakat.
Sementara awak masih berkutat dimasalah mikronya aja dan berpatok pepatah lama, “pembeli adalah raja”. Sampai sejauh mana pembeli adalah raja menjadi kenyataan?
Hehehe kalo awak tengok2 ini lebeh mirip rayuan gombal yang menghanyutkan.
Konsumen Indonesia belum mendapatkan perlindungan yang bagus sebagaimana seorang raja.
Jangankan terlindungi, awak tengok konsumen Indonesia sering berada di posisi tawar lemah, belum merdeka menentukan barang, kualitas dengan syarat-syarat yang diinginkan.
Seharusnya produsen tidak seenaknya menjejalkan barang maupun jasanya. Apalagi berupa pelayanan maupun barang busuk, teknologi usang, tidak peduli kesehatan, dan sebagainya.
Belum lagi kebijakan2 ekonomi yg makin terbuka perusahaan global berlomba masuk ke Indonesia. Bisa jadi di mata mereka Indonesia adalah pasar yang menarik, pasarnya seksi sehingga apapun barang dan jasa diusahakan masuk ke negeri ini sebagai negara konsumen.
Dari semua hal itu, alih-alih terlindungi, konsumen Indonesia sering berada di posisi tawar lemah. Konsumen belum merdeka. Semestinya, konsumen bisa menentukan barang yang akan dibeli sesuai strandar, bukan seenaknya menjejalkan barang-barang buruk, teknologi usang, tidak peduli kesehatan, dan sebagainya.
Sekarang awak coba tengok, apa negara peduli dengan rakyatnya sebagai konsumen agar terlindungi? Ada juga laaa, kita sudah punya Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Tapi kata abang awak itu, UUPK itu udah cukup usang, umurnya sudah 20 tahun, sementara kemajuan teknoligi, pasar dan jasa melesat secepat bandwidth internet (hehehe ada yg super cepat tapi di tempat tertentu masih lemot juga laaa).
Keknya, macam kata pakar, UUPK itu sudah perlu memihak pada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha/penyedia jasa, perlu dirinci sesuai dengan perkembangan jaman, ada soal barang bergerak dan tak bergerak, berwujud, dan profesionalisme untuk jasa.
UUPK perlu menjelaskan secara rinci tanggung jawab pelaku usaha barang dan jasa.
Juga dah perlu merancang perjanjian baku dan klausula baku. Perlunya kontrak yang dilakukan dalam e-commerce agar melindungi konsumen, termasuk aturan digital kontrak karena banyak transaksi online.
Tentunya tanpa melupakan masalah penyelesaian sengketa konsumen atau kelembagaan perlindungan konsumen.
Dalam hal perlindungan konsumen ini jangan laaa kita kalah dibanding Malaysia dan Thailand.
Malaysia misalnya, ada badan DSM (Departement of Standards Malaysia) dengan mandat melipatgadakan kualitas hidup rakyat Malaysia agar berdaya saing global untuk produk & jasa Malaysia.
Termasuk di dalamnya objektifnya melindungi konsumen. DSM didukung lembaga riset bernama SIRIM yang fokus melakukan kajian standard industri.
Thailand juga memiliki lembaga serupa yakni TISI (Thai Industry Standard Institute) berada di bawah Kementerian Perindustrian.